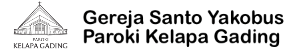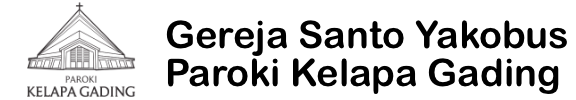DI BEBERAPA keuskupan, seorang imam disapa dengan sebutan “Romo” (biasanya ditulis: “Rama”). Bahkan seorang calon imam pun sudah disapa “Romo (Muda)”. Saya bukan orang Jawa, tetapi pernah belajar secara privat dengan orang yang mengerti budaya Jawa ketika dulu menjalani novisiat di Yogyakarta. Sapaan ini sudah menjadi lazim, sehingga cenderung dilupakan makna aslinya. Akan tetapi ungkapan Romo pun turut membentuk cara bicara dan sepak terjang seorang imam. Sebutan “romo” di kalangan masyarakat jawa berasal dari lingkungan “kraton” yang “foedal”. Seorang anak mengungkapkan penghormatan kepada ibunya dengan sapaan kanjeng Ibu dan kepada ayah kanjeng Romo, yang mengungkapkan hubungan yang formal, resmi, kaku dan berjarak. Bukan hanya anak memberi hormat kepada ayah-ibunya tetapi setiap orang harus saling menghormati. Mengapa demikian?
Dalam masyarakat Jawa setiap orang ketika saling berhadapan harus memberikan sikap hormat dalam cara bericara dan membawa diri. Ungkapan diri dan bahasa disesuaikan dengan derajat dan kedudukan lawan bicara. Semua hubungan ditata secara hierarkis, maka orang yang berkedudukan lebih tinggi diberi hormat. Di lain pihak kepada yang lebih rendah diperlihatkan sikap kebapaan dan keibuan yang bertanggung jawab dan mengayomi. Demikianlah dalam bahasa jawa dikenal tingkatan tutur: ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu dan kromo alus. Dalam setiap pembicaraan, orang harus mengakui kedudukan orang lain dengan beri sikap hormat yang terungkap dalam bahasa, sikap dan gerak gerik. Sikap hormat sering cenderung menjadi sikap takut (wedi), malu (isin) dan malu-malu (sungkan). Dalam bicara harus sungguh diperhatikan pangkat dan kedudukan. Bahasa “krama” mengungkapkan sikap hormat sedangkan tutur ”ngoko” cenderung mengungkapkan keakraban. Ketika berbicara dalam bahasa jawa kita harus sadar betul akan kedudukan sosial setiap orang. Jelaslah, sapaan romo bagi seorang imam pada kedudukan hierarkis yang lebih tinggi dan memberi hormat dalam tutur kata, sikap dan gerak-gerik. Seseorang yang datang dari desa yang bercorak sosial egaliter, Ketika menjadi imam disapa “romo”, sebuah istilah dari lingkungan kraton. Secara sosial kedudukannya lebih tinggi di mata umat dan masyarakat Jawa.
Di zaman ini cukup banyak orang dan beberapa ilmuwan mengkritisi sikap hormat dari budaya jawa, sikap hormat cenderung menjadikan komunikasi atasan-bawahan dan tidak sejati. Orang merasa kurang bertanggung jawab, laporan dibuat “asal bapa senang”. Ketika perundingan peserta menyatakan persetujuan tetapi belum tentu putusan rapat dilaksanakan. Sikap hormat tidak menjamin ketaatan. Namun demikian sikap hormat bernilai positif pula. Tidak setiap situasi dituntut sikap hierarkis. Apalagi kehidupan di desa sangat menjunjung tinggi nilai kesamaan (egaliter). Sikap hormat pun diperlukan demi kehidupan yang rukun dan selaras. Semua hal sudah teratur pada tempatnya masing-masing.
Ketika belajar di Seminari Menengah di Jawa saya mengalami dan merasakan sikap hormat daerah lokal setempat. Bersama seorang imam selama liburan, kami mengunjungi umat di desa. Imam diterima dengan sikap hormat, diberi tempat duduk yang istimewa dan makan pun disajikan secara khusus. Dengan sopan umat mendengarkan wejangan dari imam disertai dengan senyuman. Umat menanggapi dengan lebih banyak kata “Ya”. Bagi saya pengalaman ini luar biasa dan memperkaya pemahaman saya akan macam ragam budaya Indonesia.
Itulah alasan mengapa, setelah ditahbiskan menjadi imam untuk KAJ, saya menganjurkan umat untuk menyapa saya dengan “Pastor” saja. Sebutan “pastor” sangat biblis, dan Kitab Hukum Gereja pun, mengunakan istilah “pastor” untuk seorang imam. Dalam penugasan resmi dari pihak Keuskupan atau Uskup, juga menggunakan sebutan “pastor”.
Dalam bahasa latin “pastor” berarti Gembala. Dalam Perjanjian Lama istilah Pastor ditunjukan kepada para pemimpin (Yer. 2: 8; 3: 15). Juga ditunjukan pada Allah sebagai Gembala yang baik (Yeh. 34: 1-31; Mzm. 23: 1-4). Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyebut diri-Nya sebagai Gembala yang Baik menyerahkan hidup untuk domba-domba-Nya. (Yoh. 10: 11-16; Ibr. 13: 20; 1 Ptr. 2 :25). Yesus pun memanggil orang lain menjadi “gembala” dalam Gereja, tetapi umat tetaplah domba-domba-Nya (Yoh. 21: 15-17; 1 Ptr. 5: 1-4)
Menurut konsili Vatikan II “para imam berdasarkan Sakramen Tahbisan: ditahbiskan menurut citra Kristus, Iman Agung yang abadi (Ibr. 5: 1-10; 7:24; 24; 9:11-28) untuk mewartakan injil serta menggembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi, sebagai imam sejati Perjanjian Baru. (LG. No.28) sebagai pembantuan para uskup, para imam memimpin, menguduskan dan membimbing umat, mereka melaksanakan tugas memimpin dan mengikuti teladan Yesus, Gembala Baik. Yesus, Sang Gembala Agung: yang datang tidak untuk dilayani melainkan untuk melayani (Mat. 20: 28; Mrk. 10:45) (LG.27). Para Imam dalam tugas kerasulan hendaknya bekerja sama secara persaudaraan dengan kaum awam para imam hendaknya dengan tulus mengakui nilai pengalaman maupun kecakapan menerka diperlbagai bidang kegiatan manusia, supaya bersama mereka mampu mengenali tanda-tanda zaman” (PO,9).
Nah, jelaslah kepemimpinan hierarkis dalam masyarakat foedal tentu berbeda dengan kepemimpinan dalam Gereja menurut konsili Vatikan II. Kepemimpinan seorang Romo menurut budaya lokal bisa saja berbeda dengan kepemimpinan seorang Pastor, yang dijiwai oleh semangat pembaruan konsili Vatikan II. Pastor Paroki menggembalakan umat dari pelbagai kalangan budaya. Romo Mangun pernah menyatakan: “Ini tidak mudah di Indonesia yang didominasi oleh kebudayaan Jawa. Orang jawa mengalami kesulitan psikologis keturunan bila menghadapi kebenaraan, the Truth. Bagi orang jawa Tradisional, yang benar ialah yang menyenangkan, yang tidak membuat heboh, yang tidak bikin repot. Kebenaran selalu manis yang tidak manis pasti bukan yang benar padahal yesus bersabda ‘Aku adalah jalan, kebenaran dalam hidup’ (Yoh 14:6) dan kebenaran amat sering pahit, biasanya harus ditegakan dengan penderitaan dan salib” (Y.B Mangunwijaya, Pr. 1999. Gereja Diaspora. Yogyakarta: Kanisius, Hal. 64).
Sebagai catatan kecil, saya tidak pernah melarang siapa pun yang memanggil saya dengan sebutan “Romo” atau “Rama”. Yang penting adalah kalau menyebut saya sebagai “romo” perlu dipahami maknanya sama dengan sebutan: “pastor”. Akhirnya, semua istilah bisa berkembang dan maknanya bisa diberi arti lain yang berbeda dari arti asli. Sebagai imam boleh panggil saya “pastor”, tapi juga boleh panggil saya “romo”, bahkan sebutan lain yang lebih egaliter !